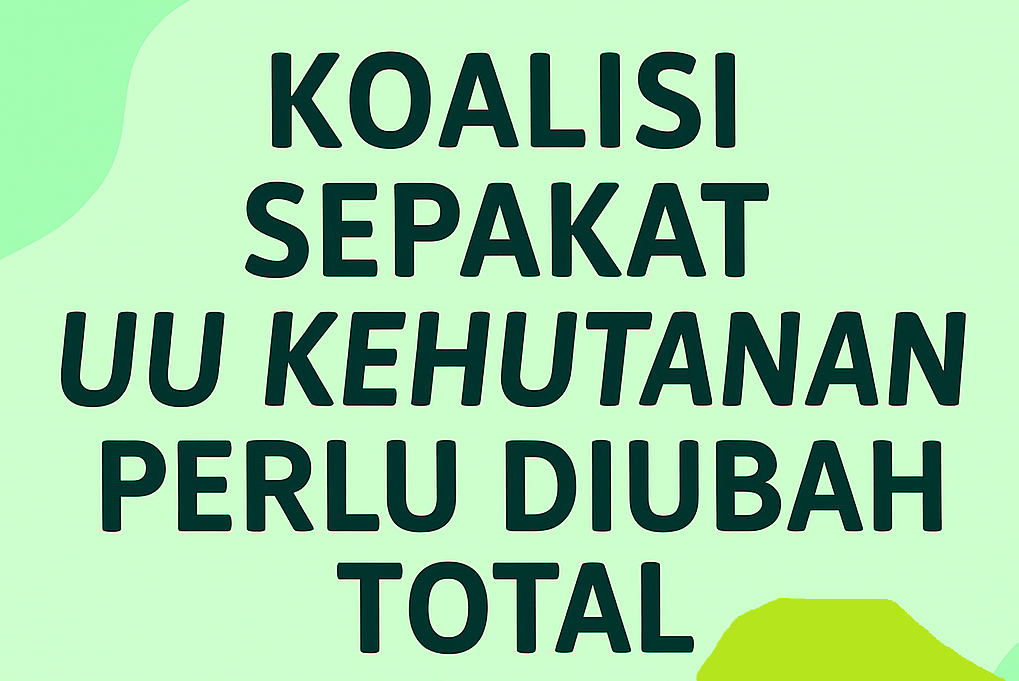UU Kehutanan dianggap kolonial dan tidak lagi relevan dengan tata kelola hutan, lahan, dan lingkungan.
14 Juli 2025 | 21.19 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang kehutanan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 25 Juni 2025. Dalam rapat tersebut Komisi IV mendengarkan aspirasi, masukan, dan saran terkait Penyusunan RUU tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tempo/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan yang terdiri dari 27 organisasi kemasyarakatan sepakat UU Kehutanan diubah secara keseluruhan. UU Kehutanan dianggap kolonial dan tidak lagi relevan dengan tata kelola hutan, lahan, dan lingkungan.
“Terdapat tiga alasan mengapa UU Kehutanan perlu direvisi total, bahkan diubah secara keseluruhan, yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis,” kata Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Patra Prayoga.
Secara filosofis, menurutnya, UU Kehutanan atau UU 41 Tahun 1999 itu tidak lagi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, spesifik pada bagian huruf (a) yang menggunakan frasa merupakan kekayaan yang dikuasai negara.
Kemudian, UU itu juga menggunakan Pasal 33 UUD 1945 dan UU 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang lekat dengan dua hal. “Konsep hak menguasai negara dan frasa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya pada saat media brief secara daring pada Senin, 14 Juli 2025.
Anggi mengatakan paradigma hak tanah dikuasai negara itu sangat berpaku pada teori politik hukum kolonial Belanda yang menganggap seluruh tanah milik raja yang kemudian milik Belanda sesuai hak milik menurut hukum barat.
“Pemerintah kolonial kemudian bisa mengusir bahkan mengkriminalisasi siapa pun yang berada di dalam tanah negara tanpa menghiraukan hak dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, peraturan dijalankan dengan pembacaan terpisah, sehingga kata-kata milik negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pada bagian menimbang huruf (a) tidak terlaksana. “Kita bisa lihat, selama 26 tahun UU itu dijalankan, sistem membuat koorporasi berskala besar yang dapat mengakses pengelolaan hutan dan gagal mencapai kemakmuran rakyat yang dimaksud,” jelasnya.
Bahkan, menurutnya, tidak hanya menyebabkan penguasaan sumber daya yang timpang pada korporasi, tetapi tidak terbukti berhasil mendongkrak produktivitas, nilai ekonomi, dan kelestarian itu sendiri.
Dia mengatakan luas kawasan hutan yang dibebani izin koorporasi berskala besar mencapai 37,6 juta hektare, sedangkan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan angkanya mencapai 8.514.921 hektare hingga 2022. Sementara pemberian izin akses masyarakat atas hutan melalui skema perhutanan sosial (PS) hanya 5.415.122 hektare atau 9.472 unit yang terdistibusi kepada 1.232.961 kepala keluarga.
“Perbandingannya sangat jauh berbeda dengan pemberian status melalui hutan adat, hanya 332.505 hektare atau 156 unit SK saja atau setara dengan 1,3 persen dari potensi hutan adat yang sudah terdata,” jelasnya.
Bukan hanya terlalu kecil dan terlambat, menurutnya, capaian di atas gagal mendorong kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dalam ekonomi perhutanan sosial umumnya terbatas pada tahap pasca-panen dan sangat minim dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan kelembagaan. “Faktanya, rumah tangga di desa-desa sekitar hutan sekitar 25.863 desa justru merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling miskin di Indonesia,” katanya.
Anggi menambahkan, UU Nomor 41 Tahun 1999 seharusnya juga memliki landasan sosiologis yang kuat, sehingga persoalan sosial, budaya, dan sejarah masyarakata adat dan petani yang telah lama hidup dan bergantung pada hutan dapat terjamin. “Hutan di Indonesia bukan hanya persoalan ekologis dan administratif saja,” katanya.
Selama 26 tahun pelaksanaan UU itu, menurutnya, kerap abai dengan beberapa hal, seperti pengabaian terhadap pemaknaan hutan bagi amsyarakat adat, pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal, konflik agraria di wilayah adat terjadi berkepanjangan, dan penertiban lahan dilakukan secara korup. “Salah satunya skema administrasi keterlanjuran dan amnesti hutan tidak berhasil menyelesaikan kerusakan hutan yang kadung hancur,” katanya.
Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman mengatakan setidaknya terdapat 687 konflik agraria berimbas kerusakan hutan seluas 11,07 hektare dan mengakibatkan 925 masyarakat adat didiskriminalisasi.
“Kita perlu mengganti UU Kehutanan itu. UU itu sudah berpengalaman terkait keterlibatan militer dalam perampasan hak masyarakat, seperti kasus Rempang dan berbagai kasus konflik lahan lainnya,” kata Arman.
Menurutnya, perluasan teritorialisasi hutan melalui kebijakan transisi energi dan pangan juga mengakibatkan banyak dampak, seperti konsolidasi lahan yang berujung pada pemanfaatan kawasan hutan dengan skala besar.
“Agenda iklim yang didorong sejak COP16 Glasgow, sebagaimana tertuang dalam National Determined Contribution Indonesia, secara khusus merencanakan deregulasi perizinan dan fasilitasi bagi proyek energi dan ketahanan pangan di kawasan hutan,” katanya.
Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Refki Saputra mengatakan hukum terkait UU Kehutanan juga dilakukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jumlah data kriminalisasi kepada masyarakat adat tidak jauh berubah sejak zaman kolonial. “Kita tahu sejarahnya selalu memposisikan petani sebagai masyarakat di sekitar atau dalam kawasan hutan yang kerap dipidana,” ujarnya.
Refki menyebut masyarakat adat dan petani menjadi dampak bias regulasi yang semena-mena selama ini. Bahkan, pemenuhan sandang, pangan, dan papan mereka bisa dipidana akibat peraturan yang cenderung berat sebelah. “Eksistensi masyarakat yang harus memiliki proteksi terlebih dahulu, namun malah mengarah ke hal sebaliknya,” katanya.
Direktur Eksekutif Women Research Institute (WRI) Sita Aripurnami mengatakan UU Kehutanan juga seharusnya diubah secara total karena masih mengandung ketimpangan gender dan eksklusi sosial dalam tata kelola kehutanan. Menurutnya, kriminalisasi masyarakat adat berdampak pada perempuan dalam keluarga.
“Penelitian Hendrastiti et al. (2024) menunjukkan perempuan lokal mulai menunjukkan kekuatan kolektif dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif, namun ketimpangan hukum masih menjadi penghalang,” katanya.
Menurutnya, UU Kehutanan tidak menjamin jaminan sosial masyarakat adat, termasuk perempuan yang ikut konflik kepemilikan lahan, sehingga tempat mereka hidup menjadi tidak terjamin. “Negara seharusnya menjamin masyarakat dan perempuan yang terkena dampak. Dampak terhadap laki-laki, perempuan, dan anak itu akan sangat berbeda-beda,” katanya.
Sementara secara yuridis, UU Kehutanan dinilai belum dapat mengatasi permasalahan hukum dan mengisi segala kekosongannya. “Bahkan setelah tujuh kali direvisi, segala masalah hukum masih belum terselesaikan,” katanya.
Sonya Andomo
Karier jurnalistiknya dimulai di media lokal dan kontributor CNNIndonesia.com untuk wilayah Sumatera Barat. Fokus liputannya pada isu gender, perbudakan gaya baru, hukum, hak asasi manusia, politik, dan lingkungan. Karya jurnalistiknya mendapat penghargaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sumber: https://www.tempo.co/lingkungan/koalisi-sepakat-uu-kehutanan-perlu-diubah-total-1995629